
Text
HUBUNGAN ANTARA NILAI CTS-6 SCORE DENGAN DERAJAT KEPARAHAN CARPAL TUNNEL SYNDROME BERDASARKAN PEMERIKSAAN ELEKTROFISIOLOGIS
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| P03246S | 370 Ban H | PERPUSTAKAAN RSUD Dr. MOEWARDI (PDF) | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
PPDS I NEUROLOGI LAB/SMF NEUROLOGI RSUD DR. MOEWARDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
- No. Panggil
-
370 Ban H
- Penerbit
- Surakarta : ., 2024
- Deskripsi Fisik
-
61 Hlm : Illus : 30 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
-
- Klasifikasi
-
370 Ban H
- Tipe Isi
-
text
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
2024
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
Carpal Tunnel Syndrome (CTS) adalah salah satu gangguan saraf tepi yang paling banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena terjadi penyempitan pada terowongan karpal, baik akibat edema fasia pada terowongan tersebut maupun akibat kelainan pada tulang-tulang kecil tangan sehingga terjadi penekanan terhadap saraf medianus di pergelangan tangan. CTS diartikan sebagai kelemahan pada tangan yang disertai nyeri pada daerah distribusi saraf medianus. Saraf medianus yang berasal dari pleksus brachialis akan melewati terowongan carpal saat berjalan dari lengan bawah menuju ke tangan (Campbell, 2019; Anindita, 2022). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika oleh National Health Interview Service (NHIS), terdapat 3,8% pada populasi umum yang diduga menderita CTS. Insiden CTS yang dilaporkan sendiri oleh pasien terus meningkat hingga 276/100.000 per tahun. CTS terjadi pada 2-5% dari populasi dunia, dan lebih sering terjadi pada wanita. Rasio wanita dan pria dengan CTS adalah 3-10 : 1 dan paling umum terjadi pada kelompok usia 4560 tahun. (Emril et al, 2019; Liong et al, 2020). Di Indonesia sendiri, kejadian CTS belum diketahui secara luas karena jumlah diagnosis CTS terbatas akibat sedikitnya jumlah pasien yang melaporkan kondisi tersebut. Selain itu juga terbatasnya sarana dan prasarana elektrodiagnostik dalam mendiagnosis CTS ini. RS Hasan Sadikin Bandung menunjukkan angka kejadian CTS sebesar 3,3% pada petugas rekam medik. Perempuan tiga kali lebih besar kemungkinan untuk menderita CTS dibandingkan laki-laki. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPNCM) menunjukkan perbandingan antara perempuan dan laki-laki sebesar 11:1, dengan kelompok usia terbanyak 51-55 tahun (Octaviana et al, 2022). CTS menjadi penyebab menurunnya jam kerja, keterampilan, dan berkurangnya pendapatan pekerja dalam waktu yang lebih lama dibandingkan cedera terkait pekerjaan lainnya. Diagnosis dini serta pemilihan terapi yang tepat berdasarkan derajat keparahan CTS diharapkan dapat mengurangi efek jangka panjang dari CTS sehingga tidak mengurangi quality of life penderita (Octaviana et al., 2022). Pemeriksaan elektrofisiologis yaitu kecepatan hantar saraf (KHS) berperan penting dalam mendiagnosis CTS dengan menunjukkan adanya penurunan kecepatan konduksi saraf medianus. Namun, tidak semua klinisi memiliki akses terhadap fasilitas elektrodiagnostik tersebut. Pemeriksaan ini juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian pasien (Schulze et al., 2021). Tidak ada konsensus yang jelas tentang kriteria diagnostik klinis terbaik untuk CTS. Salah satu pendekatan yang memiliki validitas cukup tinggi dalam diagnosis klinis penyakit ini adalah CTS-6 Score dari Graham. CTS-6 Score ini terdiri dari komponen keluhan subyektif pasien serta pemeriksaan fisik obyektif dari klinisi sehingga lebih komprehensif dalam mendiagnosis CTS (Graham, 2008; Cao et al, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Gander & Fowler (2015) menunjukkan CTS-6 Score memiliki akurasi, sensitivitas, dan spesifitas yang cukup tinggi dalam mendiagnosis CTS berdasarkan acuan pemeriksaan elektrofisiologis sebagai baku emas. Akurasi 86% untuk CTS-6 Score dinilai cukup baik, tetapi tidak cukup tinggi untuk menunjukkan bahwa CTS-6 Score dapat menggantikan pemeriksaan elektrofisiologis. Spesifisitas yang relatif rendah yaitu 80% berarti CTS-6 Score tidak berfungsi sebaik pemeriksaan elektrofisiologis sebagai uji konfirmasi yang baik. Sensitivitas yang tinggi sebesar 89% berarti CTS-6 Score dapat menjadi tes skrining yang relatif kuat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Grandizio et al. (2022) yang bertujuan untuk mengetahui reliabilitas CTS-6 Score bagi antar penilai dengan berbagai tingkat keahlian klinis menunjukkan bahwa CTS-6 Score ini dapat diandalkan sebagai alat skrining dan diagnostik CTS bagi dokter dengan berbagai tingkat pengalaman dan tanpa pelatihan khusus. Pemeriksaan elektrofisiologis secara umum juga digunakan untuk menentukan derajat keparahan dari CTS. Pemeriksaan elektrofisiologis menjadi baku emas dalam menggambarkan derajat keparahan CTS, prediksi progresivitas penyakit, dan menjadi dasar penentuan rekomendasi tatalaksana CTS (Nusrat, 2020). Terbatasnya sarana dan prasarana elektrodiagnostik di Indonesia tentunya menjadi kendala tersendiri dalam upaya menentukan derajat keparahan CTS. Meskipun CTS dapat didiagnosis secara klinis dengan alat evaluasi CTS-6 Score, hubungan antara tingkat keparahan penyakit dan nilai CTS-6 Score belum dapat dijelaskan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi nilai CTS-6 Score dengan tingkat keparahan CTS berdasarkan pemeriksaan elektrofisiologis, yaitu KHS saraf medianus pasien. Dengan adanya penelitian ini diharapkan klinisi yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas elektrodiagnostik dapat menilai hasil pemeriksaan CTS-6 Score yang didapatkan dan menghubungkannya dengan tingkat keparahan CTS.
- Pernyataan Tanggungjawab
-
dr. BANU EKO SUSANTO, NIM S552102002
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar
 Karya Umum
Karya Umum  Filsafat
Filsafat  Agama
Agama  Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu-ilmu Sosial  Bahasa
Bahasa  Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Murni 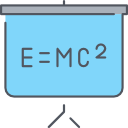 Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu Terapan 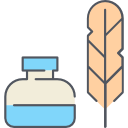 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 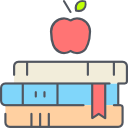 Kesusastraan
Kesusastraan  Geografi dan Sejarah
Geografi dan Sejarah